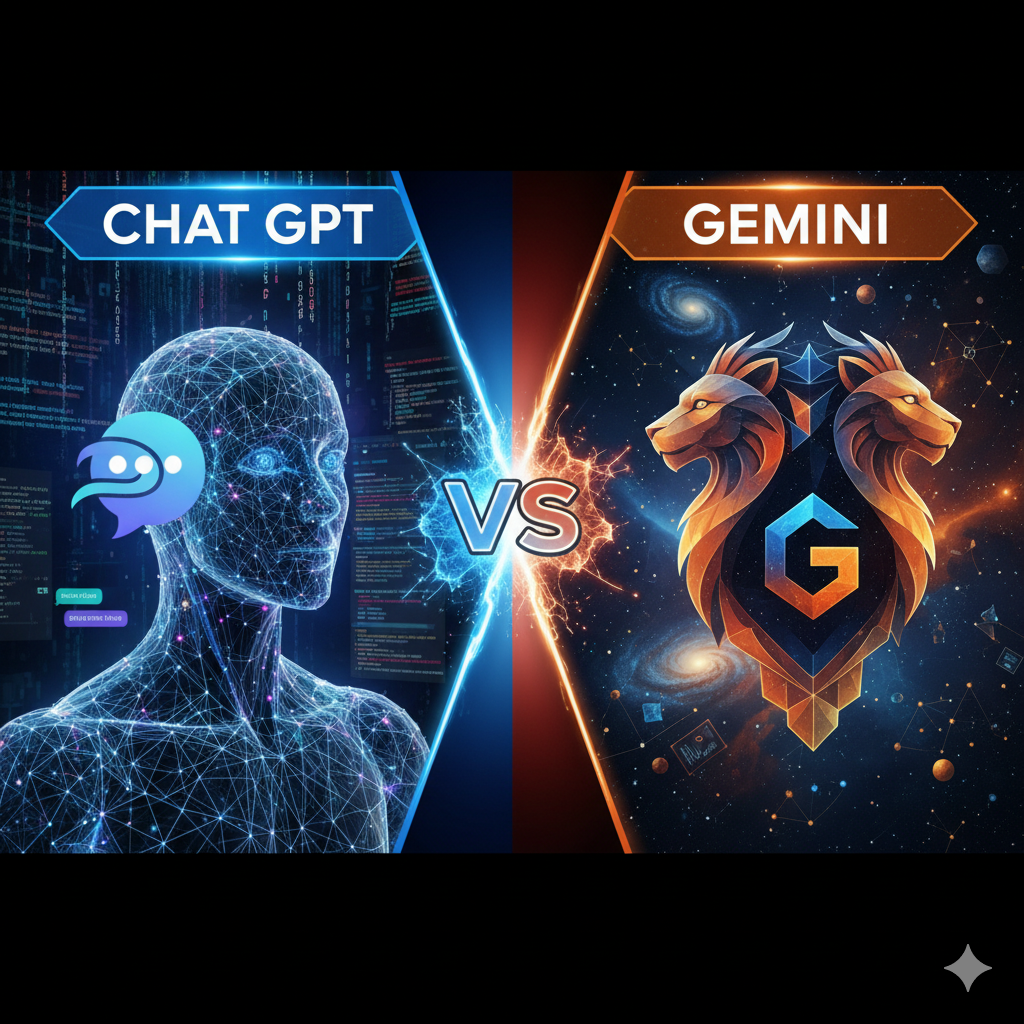Dalam Diam, Aku mendengarkan

Aku diam saja.
Bukan karena tak punya kata. Tapi karena kadang, kata tak mampu menebus kabut yang menggumpal dalam cara berpikir yang tumpul.
Temanku berkata,
tidak semua perempuan tidak tahu diri. Tidak tahu tempat. Tidak tahu cara berkata.
Dan aku mengangguk perlahan—bukan karena setuju sepenuhnya,
tetapi karena aku tahu: tidak semua luka perlu dibalut dengan perdebatan.
Ada yang, jika dituruti, bukan jadi jernih malah keruh.
Bukan jadi damai, malah semakin gaduh.
Bukan karena niatnya buruk, tapi karena pikirnya pendek.
Bukan karena hatinya gelap, tapi karena penerangnya kecil.
Kadang orang menuntut banyak bukan sebab serakah,
melainkan karena tidak paham batas.
Dan tak semua yang tak tahu batas itu jahat.
Sebagian hanyalah orang-orang yang belum selesai memahami dirinya sendiri.
Maka aku belajar mendengar, tanpa segera membalas.
Karena kadang, yang perlu bukan bantahan, tapi ruang hening
agar gema dari kesadarannya sendiri bisa kembali ke telinganya.
Aku tahu, dunia ini bukan milik lelaki saja. Bukan pula milik perempuan semata.
Tapi siapa pun yang tak mampu menakar rasa—laki-laki atau perempuan—
bisa menjelma badai kecil dalam cuaca batin orang lain.
Bukan maksud merendahkan.
Sebaliknya, ini pengingat:
bahwa timbang rasa bukan lahir dari kecerdasan mulut,
tapi dari kejernihan hati.
Dan andai pun benar sebagian dari mereka sulit diajak berpikir,
aku tidak ingin membenci.
Sebab barangkali, di balik kelemahan itu, ada luka yang belum sembuh.
Ada cerita yang belum selesai.
Ada ketakutan yang tak diungkapkan.
Aku diam saja.
Karena diam bukan kekalahan,
tapi cara paling halus untuk tetap menghargai yang tak tahu cara menghargai.
Dan dalam diam itulah aku belajar,
bahwa tidak semua harus dibenarkan,
tapi semuanya bisa dimaafkan—
jika hatimu sudah cukup lapang.
Tags:
Komentar Pengguna
Recent Berita

Presiden Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Seikh Me...
15 Okt 2025
Dinamika Politik dan Militer dalam Perang Dun...
15 Okt 2025.png)
Cuan dari Hobi, Mitos atau Fakta?
15 Okt 2025
Sebut Pesantren punya Jasa Besar bagi Bangsa...
15 Okt 2025.png)
Menulis Cerpen, Jalan untuk Menemukan Bakat T...
15 Okt 2025
Dalam Rangka Lindungi Santri, Pemerintah akan...
15 Okt 2025
Salah Satu Stasiun TV Nasional Tuai Polemik U...
15 Okt 2025
Komitmen Pemerintah Lindungi Santri dan Perku...
15 Okt 2025
Wujudkan Kesejahteraan Pesantren dan Rumah Ib...
15 Okt 2025.png)
Segar dan Sehat: Kenali Buah yang Kaya Manfaa...
14 Okt 2025.png)
Bisnis Kuliner Kekinian yang Selalu Laris Man...
14 Okt 2025
BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur:...
14 Okt 2025
Pecinta Kucing harus Tahu! Ini Manfaat Memeli...
13 Okt 2025
Lakukan Pertemuan bersama Wapres dan Jajaran...
13 Okt 2025
Apakah Privasi Masih Ada di Dunia Serba Onlin...
13 Okt 2025
Era Konten Instan: Ketika Semua Orang Jadi Kr...
13 Okt 2025
Dunia Nyata vs Dunia Digital: Batas yang Sema...
13 Okt 2025
Bentuk Perhatian Negara, Wamenag Serahkan San...
13 Okt 2025.png)
Sebelum Belanja, Tanyakan: Aku Butuh atau Cum...
13 Okt 2025