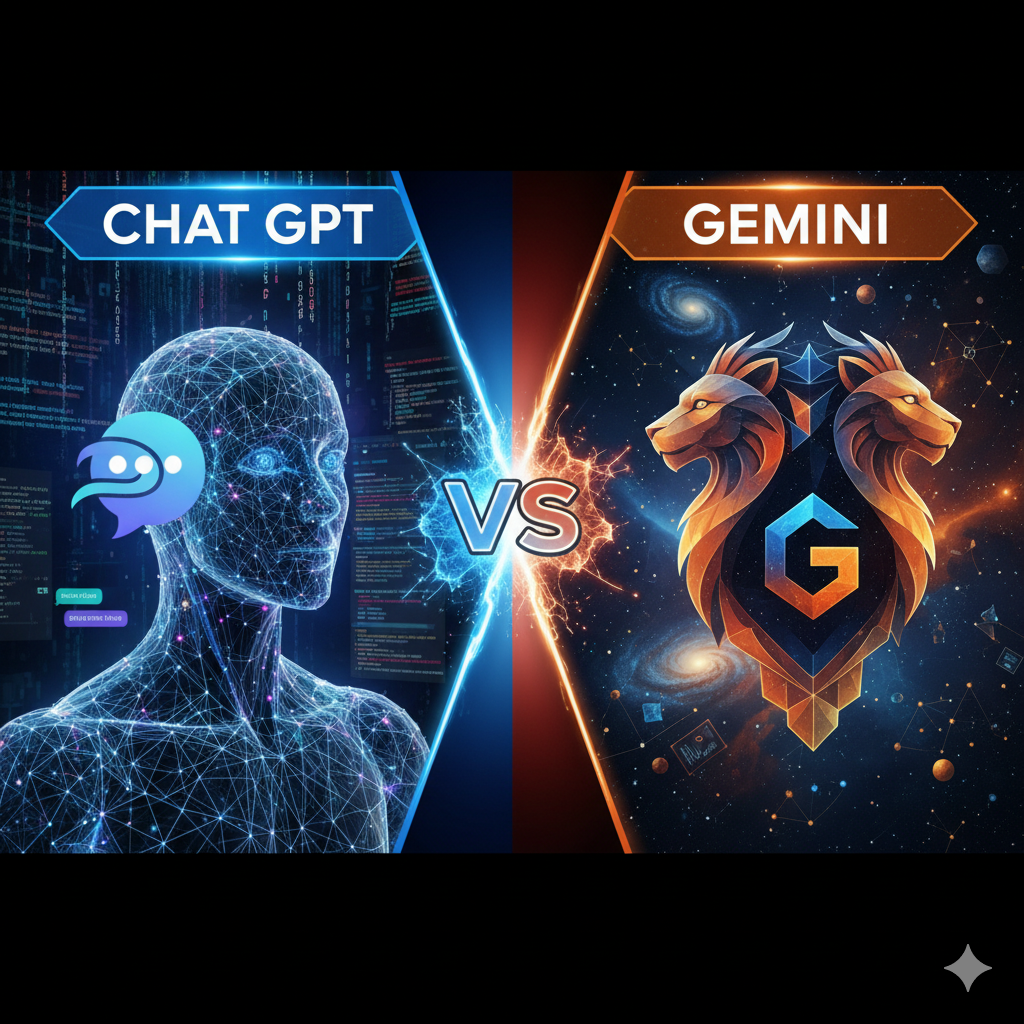Di atas mimbar yang Rapuh

Orang-orang biasa bisa jatuh di trotoar dan tak ada yang peduli. Tapi seorang pemimpin terpeleset lidah sedikit saja, bisa disiarkan berulang-ulang seolah itu bagian dari kitab undang-undang yang keliru dikutip.
Menjadi tokoh, berarti bersedia kehilangan hak atas ketenangan. Segala yang dulu dianggap sepele, kini dibedah, dianalisis, dan—jika perlu—diperkarakan. Bukan hanya sikap dan keputusan, bahkan gestur, cara tertawa, hingga nada batuknya pun bisa menjadi tafsir politik.
Namun bukan berarti dunia ini penuh pembenci. Kadang, perhatian memang tak bisa memilih bentuknya. Ia bisa berupa pujian, tapi juga bisa berupa sorak yang menghujat. Dan keduanya datang dari sumber yang sama: mata yang selalu menatap ke atas.
Menjadi pemimpin bukan berarti harus sempurna. Tapi ia harus kuat menanggung tafsir dari kekurangannya. Karena apa yang pada orang biasa disebut “manusiawi”, pada seorang tokoh sering dianggap “cacat moral”. Apa yang pada kita disebut “khilaf”, pada mereka diberi nama “bukti kebobrokan”.
Maka tidak adil menuntut pemimpin bebas dari cela. Tapi adil pula bila rakyat ingin ia lebih waras dari yang dipimpinnya. Karena itulah makna diangkat: bukan sekadar tinggi kedudukannya, tapi juga lebih dalam pemikirannya.
Kita, orang biasa, bisa berteriak sepanjang jalan tanpa masuk berita. Bisa loncat-loncat di tengah keramaian dan hanya dilihat sebagai hiburan kecil sore hari. Tapi para tokoh—berjalan saja harus dengan takaran. Diam pun harus ada maknanya.
Barangkali itulah sebabnya sebagian orang memilih tidak menjadi siapa-siapa. Karena hidup yang tenang kadang lebih nikmat daripada disorot terang dan digugat terus-menerus. Tapi dunia butuh pemimpin, meski harus kehilangan hak untuk sekadar menjadi manusia biasa.
Mas DWY
Tags:
Komentar Pengguna
Recent Berita

Presiden Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Seikh Me...
15 Okt 2025
Dinamika Politik dan Militer dalam Perang Dun...
15 Okt 2025.png)
Cuan dari Hobi, Mitos atau Fakta?
15 Okt 2025
Sebut Pesantren punya Jasa Besar bagi Bangsa...
15 Okt 2025.png)
Menulis Cerpen, Jalan untuk Menemukan Bakat T...
15 Okt 2025
Dalam Rangka Lindungi Santri, Pemerintah akan...
15 Okt 2025
Salah Satu Stasiun TV Nasional Tuai Polemik U...
15 Okt 2025
Komitmen Pemerintah Lindungi Santri dan Perku...
15 Okt 2025
Wujudkan Kesejahteraan Pesantren dan Rumah Ib...
15 Okt 2025.png)
Segar dan Sehat: Kenali Buah yang Kaya Manfaa...
14 Okt 2025.png)
Bisnis Kuliner Kekinian yang Selalu Laris Man...
14 Okt 2025
BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur:...
14 Okt 2025
Pecinta Kucing harus Tahu! Ini Manfaat Memeli...
13 Okt 2025
Lakukan Pertemuan bersama Wapres dan Jajaran...
13 Okt 2025
Apakah Privasi Masih Ada di Dunia Serba Onlin...
13 Okt 2025
Era Konten Instan: Ketika Semua Orang Jadi Kr...
13 Okt 2025
Dunia Nyata vs Dunia Digital: Batas yang Sema...
13 Okt 2025
Bentuk Perhatian Negara, Wamenag Serahkan San...
13 Okt 2025.png)
Sebelum Belanja, Tanyakan: Aku Butuh atau Cum...
13 Okt 2025