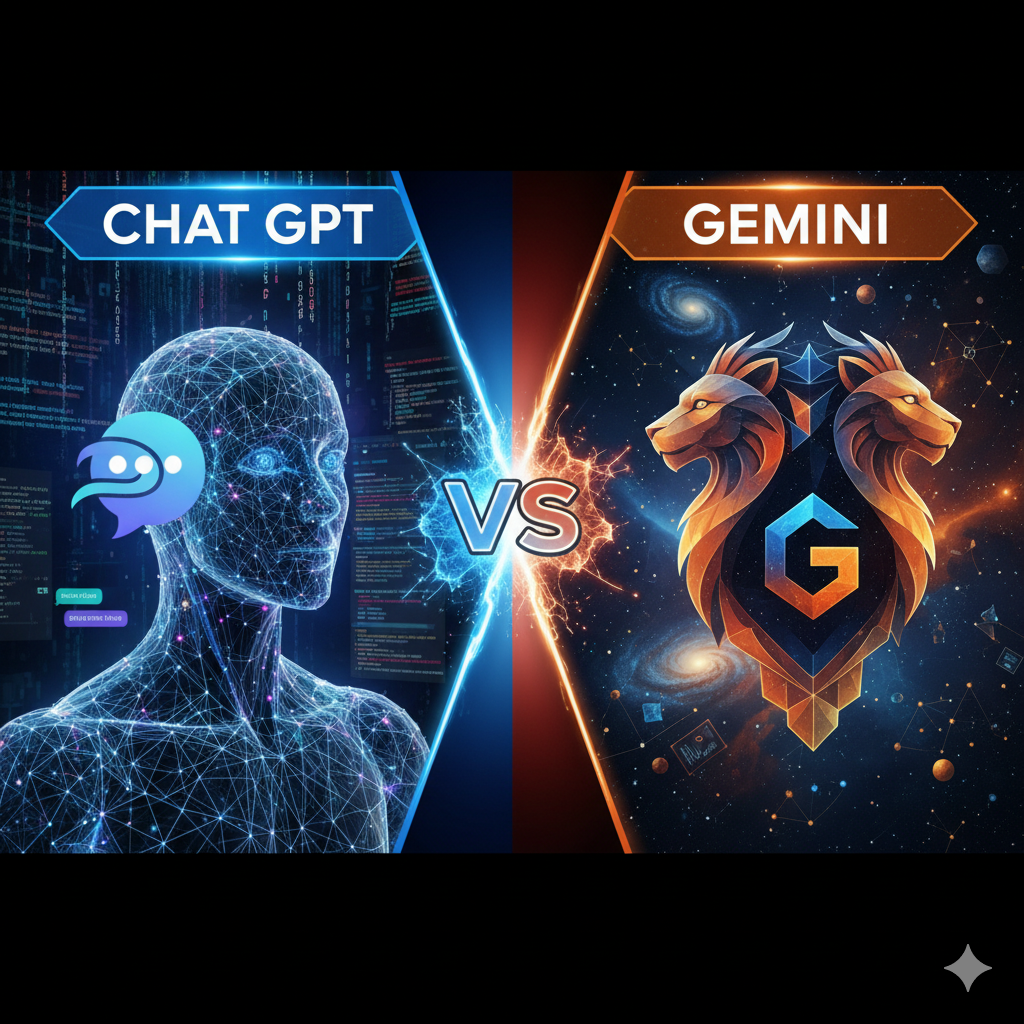Kurir

Kurir
Mari kita bayangkan sebuah dunia distopia. Dunia di mana seseorang datang ke rumah Anda, mengantarkan barang pesanan Anda, tepat waktu, lengkap, dan sesuai alamat. Tapi kemudian ia dimaki, dicurigai, bahkan difitnah, hanya karena barangnya tidak seperti yang Anda ekspektasikan. Bukan rusak, bukan hilang, bukan telat. Cuma… tidak sesuai imajinasi Anda. Dan Anda merasa paling benar karena, ya, Anda pelanggan. Yang konon katanya raja.
Inilah nasib kurir zaman ini. Ia bukan penjual, bukan pemilik toko, bukan pihak produsen. Tapi dialah yang diseret ke tengah pusaran kekecewaan pelanggan yang temperamennya lebih meledak dari diskon 11.11. Semua emosi tumpah pada satu sosok: kurir. Karena yang lain hanya akun anonim di marketplace, sedang kurir nyata berdiri di depan pagar rumah Anda. Tangannya membawa paket. Matanya berharap tidak dimaki hari ini.
Lucunya, masyarakat kita — yang sebagian besar merasa tidak perlu belajar karena merasa sudah mengerti — sering menganggap kurir itu seperti duta resmi produsen. Bahkan semacam sales sekaligus customer service berjalan. Kalau paketnya jelek, kurirnya harus minta maaf. Kalau salah warna, kurir harus menjelaskan. Kalau barangnya tidak sesuai gambar, kurir harus bertanggung jawab. Dan jika pembeli sedang stres, maka kurir adalah penebus dosa segala algoritma digital.
Padahal tugas kurir, secara sederhana dan terang benderang, hanyalah: mengantarkan barang dari titik A ke titik B sesuai sistem. Tidak lebih. Mereka tidak ikut memilih barang, tidak membungkusnya, tidak menciptakan produknya.
Tags:
Komentar Pengguna
Recent Berita

Presiden Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Seikh Me...
15 Okt 2025
Dinamika Politik dan Militer dalam Perang Dun...
15 Okt 2025.png)
Cuan dari Hobi, Mitos atau Fakta?
15 Okt 2025
Sebut Pesantren punya Jasa Besar bagi Bangsa...
15 Okt 2025.png)
Menulis Cerpen, Jalan untuk Menemukan Bakat T...
15 Okt 2025
Dalam Rangka Lindungi Santri, Pemerintah akan...
15 Okt 2025
Salah Satu Stasiun TV Nasional Tuai Polemik U...
15 Okt 2025
Komitmen Pemerintah Lindungi Santri dan Perku...
15 Okt 2025
Wujudkan Kesejahteraan Pesantren dan Rumah Ib...
15 Okt 2025.png)
Segar dan Sehat: Kenali Buah yang Kaya Manfaa...
14 Okt 2025.png)
Bisnis Kuliner Kekinian yang Selalu Laris Man...
14 Okt 2025
BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur:...
14 Okt 2025
Pecinta Kucing harus Tahu! Ini Manfaat Memeli...
13 Okt 2025
Lakukan Pertemuan bersama Wapres dan Jajaran...
13 Okt 2025
Apakah Privasi Masih Ada di Dunia Serba Onlin...
13 Okt 2025
Era Konten Instan: Ketika Semua Orang Jadi Kr...
13 Okt 2025
Dunia Nyata vs Dunia Digital: Batas yang Sema...
13 Okt 2025
Bentuk Perhatian Negara, Wamenag Serahkan San...
13 Okt 2025.png)
Sebelum Belanja, Tanyakan: Aku Butuh atau Cum...
13 Okt 2025