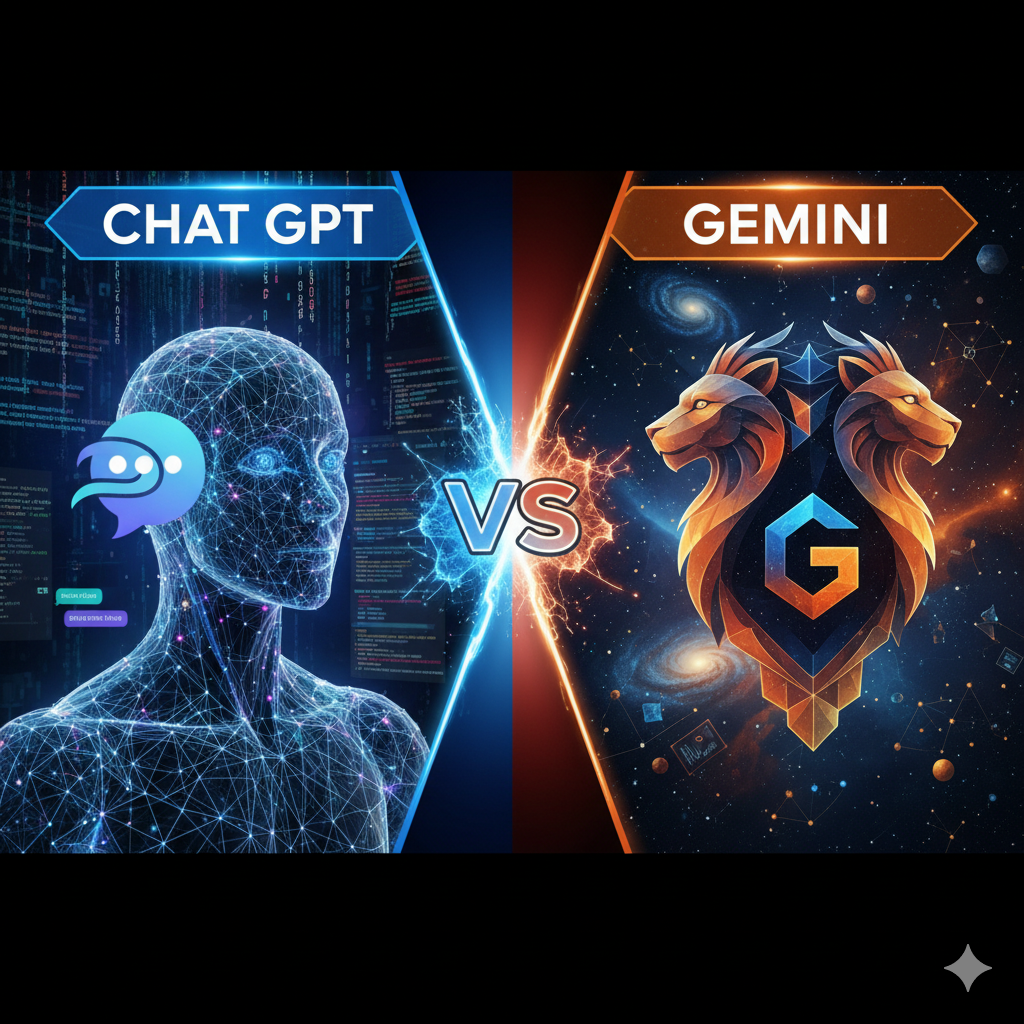Lesehan parkiran

Lesehan Pikiran
Kadang, kita harus menanggalkan kursi tinggi dan duduk di lantai.
Menurunkan frekuensi, menanggalkan keangkuhan logika,
dan ikut berpikir dari tanah—bukan dari langit.
Karena tidak semua obrolan bisa dijangkau dari menara.
Ada pikiran-pikiran yang tidak sampai jika disampaikan terlalu tinggi.
Bukan karena yang di sana tuli,
tapi karena mereka belum belajar mendengar suara yang bergema di udara yang terlalu tipis.
Kata temanku,
jika ingin dipahami, duduklah. Lesehanlah. Turunkan nada, pelankan irama.
Bukan demi merendah, tapi demi menyentuh.
Aku mulai mengerti,
mengapa para guru besar dalam sejarah justru memilih duduk bersila,
mengapa para wali lebih sering menyapa dengan cerita ketimbang dalil.
Karena mereka tahu: kebenaran yang terlalu tinggi kadang membuat orang silau, bukan tercerahkan.
Dan bukan soal pintar atau tidak,
kadang hanya soal jarak.
Kita terlalu ingin didengar, sampai lupa bahwa mereka belum siap mendengar.
Kita terlalu ingin menjelaskan, sampai lupa bahwa mereka sedang mencari bahasa yang bisa mereka cerna.
Apa gunanya berbicara dengan frekuensi yang tak bisa ditangkap?
Itu bukan komunikasi,
itu siaran kosong—gemanya hanya memantul ke dinding ego sendiri.
Maka aku belajar diam,
belajar duduk, belajar mendekat tanpa menggurui.
Karena mungkin, di lantai itu,
ada keheningan yang lebih bijak dari ribuan kalimat yang kita lontarkan dari atas mimbar.
Turun bukan kalah.
Turun adalah cara tertinggi untuk naik ke dalam hati orang lain.
Tags:
Komentar Pengguna
Recent Berita

Presiden Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Seikh Me...
15 Okt 2025
Dinamika Politik dan Militer dalam Perang Dun...
15 Okt 2025.png)
Cuan dari Hobi, Mitos atau Fakta?
15 Okt 2025
Sebut Pesantren punya Jasa Besar bagi Bangsa...
15 Okt 2025.png)
Menulis Cerpen, Jalan untuk Menemukan Bakat T...
15 Okt 2025
Dalam Rangka Lindungi Santri, Pemerintah akan...
15 Okt 2025
Salah Satu Stasiun TV Nasional Tuai Polemik U...
15 Okt 2025
Komitmen Pemerintah Lindungi Santri dan Perku...
15 Okt 2025
Wujudkan Kesejahteraan Pesantren dan Rumah Ib...
15 Okt 2025.png)
Segar dan Sehat: Kenali Buah yang Kaya Manfaa...
14 Okt 2025.png)
Bisnis Kuliner Kekinian yang Selalu Laris Man...
14 Okt 2025
BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur:...
14 Okt 2025
Pecinta Kucing harus Tahu! Ini Manfaat Memeli...
13 Okt 2025
Lakukan Pertemuan bersama Wapres dan Jajaran...
13 Okt 2025
Apakah Privasi Masih Ada di Dunia Serba Onlin...
13 Okt 2025
Era Konten Instan: Ketika Semua Orang Jadi Kr...
13 Okt 2025
Dunia Nyata vs Dunia Digital: Batas yang Sema...
13 Okt 2025
Bentuk Perhatian Negara, Wamenag Serahkan San...
13 Okt 2025.png)
Sebelum Belanja, Tanyakan: Aku Butuh atau Cum...
13 Okt 2025